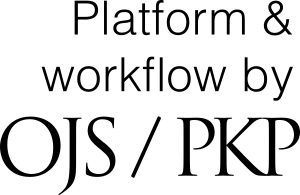Current Issue

Memaknai eksistensi seni tidak terlepas dari cara kita memandang dan menyoal keberadaan seni itu sendiri dan segala dinamika yang terjadi di dalamnya. Baik seni tradisi maupun kontemporer, persoalan eksistensi menjadi hal penting untuk melihat sejauh mana (karya) seni itu ada, tumbuh, berkembang, dan dimaknai oleh masyarakat pendukungnya. Atas dasar itu, kita perlu merenungkan kembali bahwa memandang eksistensi (karya) seni tidaklah sebatas melihat bahwa seni itu “ada”. Namun, lebih jauh dari itu, eksistensi meliputi urusan tentang bagaimana seni itu hidup, tumbuh, bertahan serta dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat pendukungnya untuk kemaslahatan hidup manusia. Pandangan ini diperkuat oleh Zaenal (2007: 16) yang mengemukakan bahwa eksistensi adalah sesuatu yang dinamis, sesuatu yang “menjadi” atau “mengada”. Dari pemahaman ini, kita bisa melihat bahwa seni tidak hadir begitu saja. Ia dibutuhkan dan dimanfaatkan makanya ia terus ada. Dalam konteks itu, perjalanan (karya) seni baik yang tradisi maupun kontemporer terus tumbuh, bergerak, dan berubah sesuai kebutuhan manusia dan perkembangan zaman. Dalam perjalanan itu, manusia memiliki peran sentral dalam menentukan eksistensi (karya) seni dan tidak jarang memakai teknologi sebagai alat bantunya. Dasar pemikiran inilah yang membawa para penulis dalam edisi Jurnal Seni Nasional Cikini terbitan Institut Kesenian Jakarta ini mengemukakan berbagai pandangan, tinjauan, dan analisis tentang bagaimana seni itu tetap ada dan bagaimana mempertahankannya. Persoalan eksistensi seni itu tercermin dalam artikel-artikel berikut yang sudah disaring oleh para editor, reviewer, dan tim redaksi yang kemudian tersaji lewat beragam topik, korpus data, metode, dan perspektif yang mereka gunakan dalam meretas eksistensi seni di tengah perubahan masyarakatnya yang dinamis. Artikel pertama ditulis oleh Muhammad Hamdanu Syakirin dengan judul “Basic Visual Components (Bruce Block) dalam Film Kain”. Ia menekankan bahwa eksistensi film salah satunya dapat dipertahankan melalui teknologi. Dalam penelitiannya, ia menunjukkan bahwa penataan basic visual components memiliki pengaruh besar dalam menggambarkan moods, emotions, dan ideas pada film Kaïn (2009) karya Kristof Hoornaert. Selain itu, ia juga memperlihatkan bahwa terdapat korelasi penataan basic visual compenents terhadap intensitas cerita. Hasil penelitiannya juga membuktikan bahwa film Kaїn mampu mengomunikasikan moods, emotions dan ideas melalui penataan basic visual components, khususnya pada elemen line dan shape dalam menyelaraskan intensitas visual dengan intensitas dramatik pada cerita, sehingga pesan dapat tersampaikan secara optimal, walau tanpa didampingi elemen suara khusus. Di samping itu, penelitiannya juga memberikan kontribusi mengenai pemahaman terhadap basic visual components dalam menyampaikan pesan menggunakan bahasa visual. Artikel berikutnya ditulis oleh Nanda Putri Mulyaningrum dan Widya Putri Ryolita dengan judul “Pemanfaatan Teknologi dalam Mengaplikasikan Gambang Kromong untuk Mewujudkan Pelestarian Budaya”. Di dalam artikelnya itu, kedua penulis ini berpendapat hampir mirip dengan penulis pertama dengan menyatakan bahwa industri musik Indonesia saat ini didominasi oleh lagu-lagu populer yang cenderung mengadopsi gaya musik Barat. Hal ini dapat menyebabkan terkikisnya eksistensi budaya musik tradisional Indonesia, dalam kasus ini penulis merujuk pada seni tradisi Gambang Kromong. Untuk itu, dalam penelitian ini, penulis berusaha mengeksplorasi cara mengaplikasikan instrumen Gambang Kromong ke dalam lagu-lagu populer dengan memanfaatkan teknologi sebagai upaya pelestarian budaya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat beberapa teknik pengaplikasian Gambang Kromong dalam lagu populer, seperti penggunaan sampel suara Gambang Kromong, aransemen lagu dengan melodi dan ritme Gambang Kromong, serta kolaborasi dengan musisi tradisional. Pemanfaatan teknologi seperti digital audio workstation, sampling, dan sintesis suara dapat membantu proses integrasi Gambang Kromong ke dalam lagu populer. Hal ini dapat menjadi strategi efektif untuk melestarikan
budaya musik tradisional Indonesia di tengah dominasi musik populer. Masih dengan korpus data Gamang Kromong, Imam Firmansyah menyorot eksistensi seni tradisi lewat tulisannya yang berjudul “Membaca Sejarah Perkembangan Gambang Kromong Melalui Karya Fotografi”. Ia memulai uraian dengan mengulas asal-usul Gambang Kromong sebagai sebuah musik tradisi masyarakat Betawi dan Cina Benteng yang berkembang melewati proses hibridisasi yang panjang antara budaya Tionghoa dengan Pribumi sejak abad ke-18. Lebih lanjut, ia menyorot proses perkembangan seni tradisi ini terdokumentasikan dengan baik melalui karya fotografi yang sebagian besar dilakukan oleh Isidore van Kinsbergen, seorang fotografer pemerintah Hindia-Belanda sejak tahun 1851. Selanjutnya, ia melakukan analisis data melalui interpretasi terhadap karya fotografi yang kemudian dikaitkan dengan analisis teks dan konteks musik Gambang Kromong. Penelitian ini menghasilkan tiga bacaan karya foto karya Van Kinsbergen dan sebuah foto anonim. Bacaan foto pertama adalah embrio Gambang Kromong yang bernama Orkest Gambang, terdiri dari ansambel kecil yang memainkan musik instrumental, dan dimainkan dalam pesta-pesta Tionghoa kelas atas. Bacaan Foto kedua adalah masuknya penyanyi perempuan yang disebut cokek yang direkrut dari pribumi. Bacaan yang ketiga adalah masuknya alat musik Indonesia dalam Orkest Gambang dan menjadi Gambang Kromong sehingga bisa turut dinikmati oleh pribumi kelas bawah. Tinjauan eksistensi seni berikutnya menyoal masyarakat Jawa dihadirkan oleh Teguh Prasetyo dan Mike Wijaya Saragih lewat tulisan berjudul “Representasi Sikap Hidup Orang Jawa dalam Pengakuan Pariyem karya Linus Suryadi AG dan Babad Ngalor Ngidul karya Elizabeth D. Inandiak”. Kedua penulis menelisik cara pandang orang Jawa melalui teks sastra. Menurutnya, dalam kesusastraan Indonesia, gambaran masyarakat Jawa seringkali dimunculkan, terutama oleh pengarang keturunan Jawa sendiri. Namun, terdapat pula beberapa gambaran orang Jawa yang muncul dari pengarang yang berasal dari luar Jawa, bahkan warga negara asing (non-Jawa). Kemudian, penulis mempertanyakan tentang bagaimana sikap hidup orang Jawa digambarkan dalam novel-novel yang ditulis oleh pengarang Jawa dan non-Jawa. Untuk itu, melalui studi komparatif, penulis mengambil dua sampel prosa Indonesia, yaitu Pengakuan Pariyem karya Linus Suryadi AG (pengarang keturunan Jawa) dan Babad Ngalor Ngidul karya Elizabeth D. Inandiak (pengarang berkewarganegaraan Prancis). Melalui dua novel ini, penulis ingin melihat gambaran sikap hidup orang Jawa dari sudut pandang penceritaan pengarang yang berbeda latar belakang budaya. Dengan melihat struktur karya, narasi, dan konsep representasi, tampak penulis ingin membedah penggambaran sikap hidup orang Jawa dari kedua pengarang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa kedua novel tersebut menggambarkan jati diri dan sikap hidup orang Jawa seperti yang seringkali ditunjukkan dalam berbagai literatur, yakni sebagai orang yang menjunjung keselarasan dan laku hidup yang mengindahkan dunia. Namun demikian, keduanya memiliki gaya penarasian yang unik, yang menunjukkan bahwa Inandiak, pengarang berkebangsaan Prancis, memiliki kecenderungan penggambaran yang bernada lebih orientalis dibanding penarasian dari karya Linus Suryadi AG sebagai orang keturunan Jawa. Kembali pada persoalan eksistensi seni tradisi Betawi, artikel selanjutnya ditulis oleh Syadiidah lewat artikelnya yang berjudul “Psikodinamika Alam Bawah Sadar Masyarakat Betawi dalam Tradisi Pembacaan Maulid Barzanji”. Penulis memulai pemaparannya melalui uraian tentang seluk-beluk tradisi pembacaan Barzanji dalam masyarakat Betawi. Menurutnya, masyarakat Betawi sebagai komunitas yang memegang teguh budaya ketimuran masih konsisten melaksanakan tradisi tersebut hingga saat ini. Hal ini menurutnya menunjukkan bahwa pembacaan Barzanji memberikan pengaruh psikologis pada setiap individu, sekalipun mereka tidak memahami bahasa Arab. Atas dasar itu, penelitian ini secara khusus membahas pengaruh pembacaan maulid Barzanji terhadap psikodinamika alam bawah sadar dalam konteks masyarakat Betawi. Melalui metode kualitatif menggunakan pendekatan etnografi penulis melihat adanya pengaruh pembacaan maulid Barzanji terhadap alam bawah sadar masyarakat Betawi. Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa superego yang terbentuk dari pemahaman terhadap makna perjuangan Rasulullah terekam ke alam bawah sadar yang memberikan ketenangan saat pembacaan dan setelahnya sebagai refleksi kecintaan umat terhadap rasulnya yang berdampak pada keinginan untuk bertemu Nabi Muhammad saw. Dengan demikian, secara tidak langsung, penulis meneguhkan bahwa pembacaan Barzanji bagi masyarakat Betawi sudah tertanam di alam bawah sadar mereka sebagai suatu kebutuhan, baik secara individual, agama, dan kemasyarakatan, yaitu kodrat manusia sebagai makhluk sosial.
Demikian pengantar redaksi pada terbitan Jurnal Seni Nasional Cikini pada edisi kali ini. Tim redaksi berharap dengan beragam analisis dan temuan para penulis dalam menyoroti eksistensi seni dapat membuka pemahaman kita tentang bagaimana cara melihat eksistensi seni dari masa lalu, masa kini, hingga masa mendatang untuk dapat melihat, memahami, dan memaknai (karya) seni sebagai warisan budaya dan sumbangan peradaban manusia.